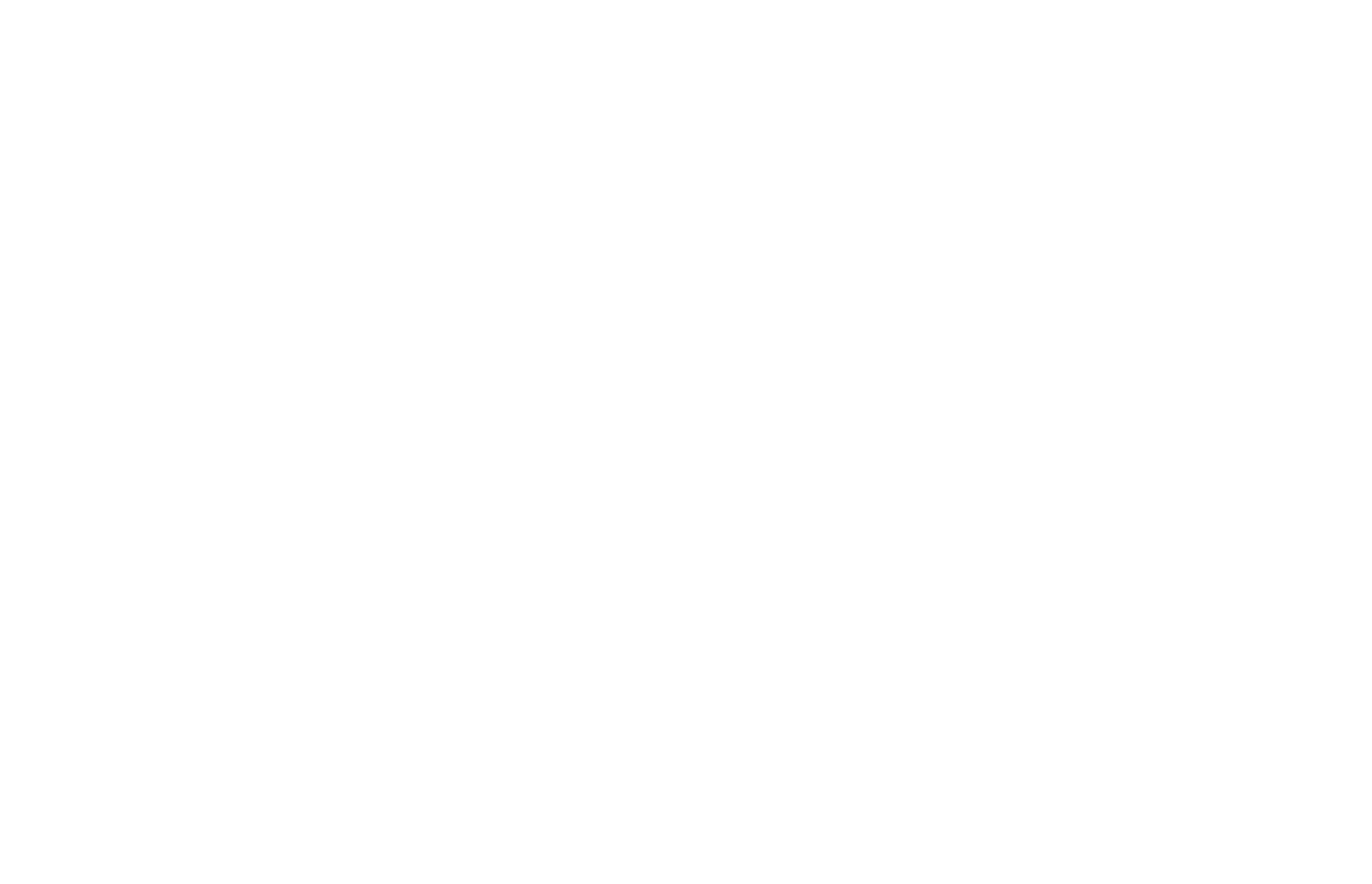23 Juli 2016, 09:07
Tantangan Agrikultur Perkotaan untuk Surabaya
Oleh : Dadang ITS |
|
Source : -
Di Surabaya, sistem pertanian perkotaan atau urban farming sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2009. Namun sayangnya kondisi yang ada saat ini sangat dipertanyakan keberlanjutannya.
Dalam seminar bertajuk Challenge of Urban Agriculture to Support Sustainable Livelihood, Jumat (22/7) ini, Dr Ir Eko Budi Santoso LicRerReg membeberkan pendapatnya.
"Jika dilihat memang miris. Data menunjukkan setiap tahunnya jumlah penggiat aktifitas ini semakin menipis. Bahkan hampir berkurang 100 tim setiap tahunnya," ungkap Eko.
Meski begitu, tambahnya, jumlah sedikit sebenarnya tidak menjadi persoalan. Asalkan kegiatan semacam ini dilakukan secara masif dan merata ke seluruh wilayah Surabaya. "Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di sini," ujar dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITS ini.
Walau terbilang baik, nyatanya kondisi urban farming di Surabaya masih di bawah target. Pemerintah menyasar angka 62,76 persen sedangkan saat ini Surabaya baru berada di angka 47 persen. "Sehingga perlu ada kebijakan lagi yang diberlakukan oleh pemerintah," tambah Eko.
Kebijakan dirasa perlu karena masih banyak masyarakat yang enggan bercocok tanam. Alasan yang paling umum diantaranya adalah banyaknya biaya tambahan yang harus dikeluarkan, seperti biaya air untuk menyiram.
Keengganan masyarakat yang demikian menyebabkan banyak pemilik lahan pertanian lebih memilih menjual lahannya kepada pengembang konstruksi. "Tercatat 80 persen lahan pertanian kini milik mereka para pengembang," papar doktor lulusan Universitas Brawijaya ini.
Mirisnya kondisi ini juga terjadi di Kampung Sambiserep, Surabaya, yang setiap tahunnya menghasilkan 6000 ton cabai merah sebagai komoditas. "Jika lahan-lahan cabai dibeli oleh para pengembang, apakah kita bisa mempertahankan jumlah tersebut?†pungkas Eko. (arn/hil)
Berita Terkait
-
Hari Raya Natal sebagai Momentum Memperkuat Toleransi
Kampus ITS, Opini — Hari Raya Natal merupakan perayaan keagamaan umat Kristiani yang setiap tahunnya dirayakan sebagai momen refleksi
23 Juli 2016, 09:07 -
Wujudkan Kampus Inklusif, ITS Matangkan Persiapan Layanan Disabilitas
Kampus ITS, ITS News — Isu aksesibilitas dan layanan disabilitas kini tengah telah menjadi perhatian serius di berbagai perguruan tinggi.
23 Juli 2016, 09:07 -
Aplikasi StrokeGuard Karya Mahasiswa ITS Resmi Digunakan di Rumah Sakit
Kediri, ITS News — Startup StrokeGuard yang didirikan oleh mahasiswa Jurusan Inovasi Digital Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menjalin
23 Juli 2016, 09:07 -
Lewat Ekspedisi OceanX-BRIN 2025, ITS Berperan dalam Eksplorasi Laut Dalam Sulawesi
Kampus ITS, ITS News – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan bangga dapat berpartisipasi dalam ekspedisi ilmiah internasional “OceanX –
23 Juli 2016, 09:07